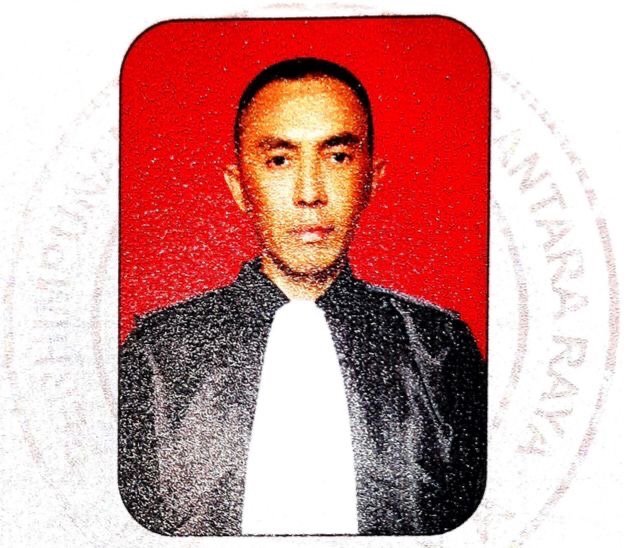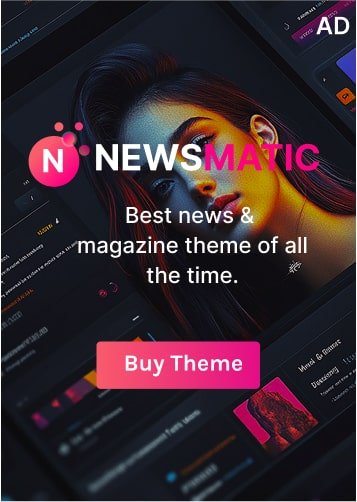Oleh: Rahim Tomia Ketua Divisi Litigasi LBH Ansor Maluku
Publik kembali disuguhi potret penegakan hukum yang menuai kontroversi. Kali ini, sorotan tertuju pada proses hukum yang tengah dihadapi Gus Yaqut. Fenomena penegakan hukum yang sarat polemik sejatinya bukan hal baru dalam lanskap hukum Indonesia. Sebelumnya, sejumlah nama publik seperti Hasto Kristianto, Tom Lembong, hingga Nadiem Makarim juga pernah terseret dalam pusaran kasus yang memantik dugaan kriminalisasi dan kental dengan aroma agenda tersembunyi (hidden agenda).
Kini, Gus Yaqut resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji tahun 2024. Dalam perkara ini, KPK menjerat Gus Yaqut dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Namun, penetapan status tersangka tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Prosesnya terkesan dipaksakan dan menyisakan banyak ketidakjelasan. Sejumlah pemberitaan media menyebutkan bahwa hingga kini KPK belum melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan yang dituduhkan kepada Gus Yaqut. Padahal, unsur kerugian negara merupakan elemen krusial dalam pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: dasar apa yang digunakan penyidik untuk menetapkan unsur “merugikan keuangan negara”? Apakah telah ada hasil penghitungan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ataukah unsur tersebut sekadar diasumsikan? Ketidakjelasan ini wajar memicu kecurigaan publik terhadap kejanggalan dalam proses hukum yang dijalankan.
Dalam doktrin hukum pidana korupsi, kerugian keuangan negara harus bersifat nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss). Aparat penegak hukum tidak dibenarkan berandai-andai dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Prinsip ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” harus dibuktikan melalui kerugian yang benar-benar terjadi.
Jika merujuk pada prinsip tersebut, maka proses hukum terhadap Gus Yaqut patut dipertanyakan validitas dan objektivitasnya. Penegakan hukum yang mengabaikan prasyarat fundamental justru berpotensi mencederai rasa keadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan indikasi bahwa prinsip fair trial belum sepenuhnya dijalankan. Padahal, dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), prinsip fair trial bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama yang wajib dijunjung tinggi sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan.
Tanpa penghormatan terhadap prinsip fair trial, penegakan hukum berisiko berubah menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan. Dan ketika itu terjadi, yang terancam bukan hanya nasib seorang individu, tetapi juga integritas hukum dan demokrasi itu sendiri.