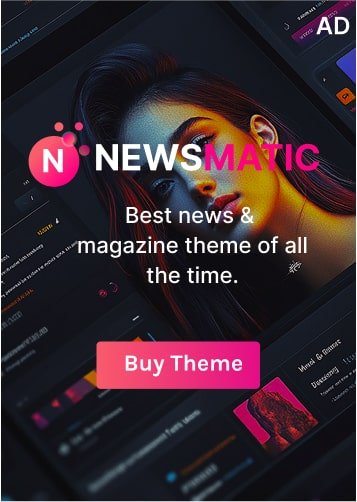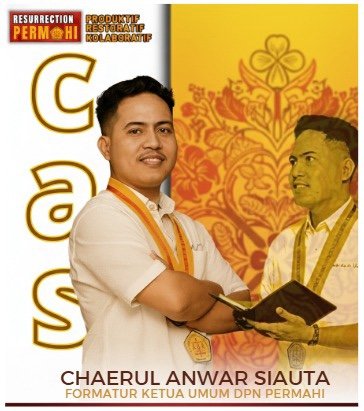Oleh Salidin Wally
Setiap 10 November, bangsa ini berkumpul di taman-taman makam pahlawan. Bendera setengah tiang berkibar, pidato digemakan, dan bunga ditaburkan. Namun setelah upacara selesai, sering kali yang tersisa hanyalah rutinitas bukan kesadaran. Hari Pahlawan seolah menjadi seremoni tahunan yang kehilangan daya refleksi. Padahal, ia mestinya menjadi ruang renung: apakah semangat kepahlawanan masih hidup di dada bangsa ini?
Dari timur Indonesia, nama Abdul Muthalib Sangadji lebih dikenal sebagai A.M. Sangadji mengajarkan bahwa kepahlawanan bukan hanya tentang perang, melainkan tentang keberanian berpikir dan bertindak untuk kemanusiaan. Lahir di tanah Maluku, Sangadji tumbuh menjadi bagian dari denyut awal kebangkitan nasional. Bersama H.O.S. Tjokroaminoto dan tokoh Sarekat Islam lainnya, ia memperjuangkan martabat rakyat melalui pena, gagasan, dan integritas moral.
Sangadji tidak memegang senjata, tapi kata-katanya tajam menembus dinding kolonialisme. Ia bicara tentang keadilan sosial dan kemerdekaan rakyat dalam forum-forum yang jarang diisi anak bangsa kala itu. Di tengah tekanan penjajahan, ia menulis, berpidato, dan berdebat untuk menyalakan kesadaran kolektif bahwa bangsa ini pantas berdiri sejajar dengan bangsa mana pun di dunia.
Namun, apa arti perjuangan itu hari ini? Ketika bangsa ini sudah merdeka secara politik, musuh yang dihadapi justru lebih halus tapi tak kalah berbahaya: kebodohan, intoleransi, dan korupsi. Jika dulu penjajah datang dari luar, kini penjajahan tumbuh dari dalam diri dari egoisme, ketamakan, dan kehilangan rasa malu.
Dalam konteks inilah semangat Sangadji menemukan relevansinya. Ia mengajarkan bahwa menjadi pahlawan tidak perlu menunggu panggilan perang. Cukup dengan bekerja jujur, berpikir merdeka, dan berani membela kebenaran ketika kebanyakan orang memilih diam. Kepahlawanan, pada akhirnya, adalah keberanian melawan arus ketidakbenaran dengan cara yang bermartabat.
Di tengah kaburnya batas antara idealisme dan pragmatisme hari ini, figur seperti A.M. Sangadji mengingatkan bahwa nasionalisme bukan soal slogan, melainkan laku hidup. Ia menulis dan berbicara untuk menyatukan, bukan memecah. Dari tanah Maluku, ia mengirim pesan sederhana: bahwa cinta tanah air adalah tanggung jawab moral, bukan sekadar kebanggaan geografis.
Hari Pahlawan seharusnya tak berhenti di tugu dan upacara. Ia mesti menjadi cermin apakah kita masih mewarisi semangat para pendahulu, atau sekadar menikmati hasil perjuangan mereka tanpa menjaga maknanya.
A.M. Sangadji telah menyalakan api dari timur. Tugas kita hari ini adalah memastikan nyalanya tak padam di tengah gelapnya zaman.