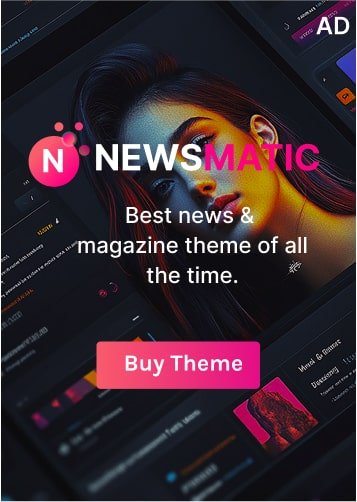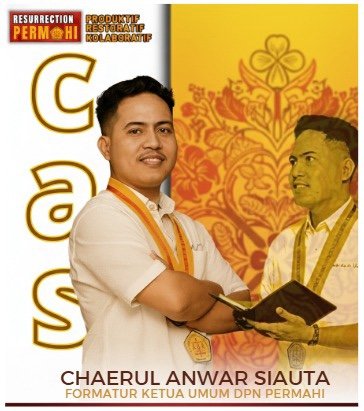Ambon – Sebuah seremoni megah di Osaka, Jepang, pada 7 Oktober 2025 lalu menandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Shanxi Sheng’an Mining Co., Ltd., perusahaan tambang asal Tiongkok, dan PT. Indonesia Mitra Jaya, perusahaan jasa asal Indonesia. MoU itu disebut sebagai langkah awal pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) proyek strategis nasional yang digadang menjadi pelabuhan terpadu terbesar di Indonesia Timur, dengan nilai investasi mencapai USD 50 juta atau sekitar Rp831 miliar.
Namun, di balik gegap gempita diplomasi bisnis itu, gejolak muncul di Negeri Kaibobu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, tempat proyek tersebut akan dibangun. Warga yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atas lahan proyek, menyuarakan keresahan karena tak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun kesepakatan kerja sama.
“Kalau memang ini proyek pelabuhan terpadu, kenapa mitranya perusahaan tambang, bukan perusahaan pelabuhan atau logistik?” tanya Mario Kakisina, alumnus Magister Hukum Universitas Pattimura dan putra asli Kaibobu, Senin (13/10).
Pertanyaan Mario menohok jantung logika publik. Shanxi Sheng’an Mining dikenal bergerak di bidang pertambangan batu bara dan kimia turunan seperti kokas dan metanol. Sementara PT. Indonesia Mitra Jaya selama ini berfokus pada jasa perawatan gedung dan penyediaan kebutuhan industri, jauh dari dunia infrastruktur pelabuhan.
Kecurigaan masyarakat Kaibobu semakin kuat setelah mengetahui bahwa penandatanganan MoU itu dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD Maluku dan DPRD SBB, dua lembaga yang secara hukum mewakili suara rakyat dalam pengawasan kebijakan pembangunan.
“Jika nilai proyeknya mencapai Rp831 miliar dan melibatkan lahan luas, mengapa prosesnya seolah dilakukan diam-diam tanpa persetujuan lembaga resmi dan masyarakat adat?” tutur Mario dengan nada kecewa.
Lebih jauh, data yang mencuat menambah kejanggalan. MoU menyebutkan lahan proyek seluas 500 hektar di Desa Waisarisa, namun menurut catatan lokal, lahan eks PT. Djayanti Group di lokasi tersebut hanya sekitar 68 hektar.
“Kalau 68 hektar saja milik eks perusahaan lama, sisanya dari mana? Apakah tanah masyarakat Kaibobu akan digarap tanpa izin?” tegas Mario.
Warga Kaibobu mengingatkan bahwa tanah petuanan mereka memiliki status hukum adat yang diakui negara. Mereka menuntut transparansi dan pelibatan penuh masyarakat adat sebelum satu meter pun tanah digusur.
“Pelibatan masyarakat bukan hanya etika, tapi kewajiban hukum. Pemerintah dan investor harus membuka komunikasi dan melakukan konsultasi publik agar investasi tidak berujung konflik,” tambahnya.
Kini, publik menanti kejelasan dari pemerintah pusat dan daerah: apakah proyek senilai ratusan miliar rupiah ini benar-benar untuk kepentingan rakyat Maluku, atau hanya bagian dari agenda bisnis global yang menempatkan masyarakat adat sebagai penonton di tanah sendiri.